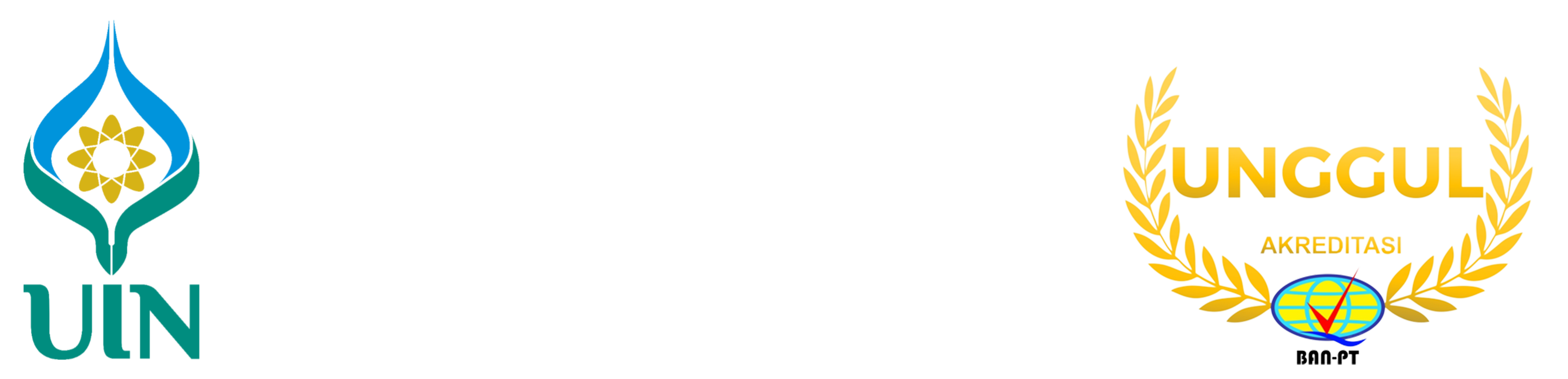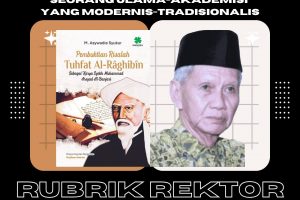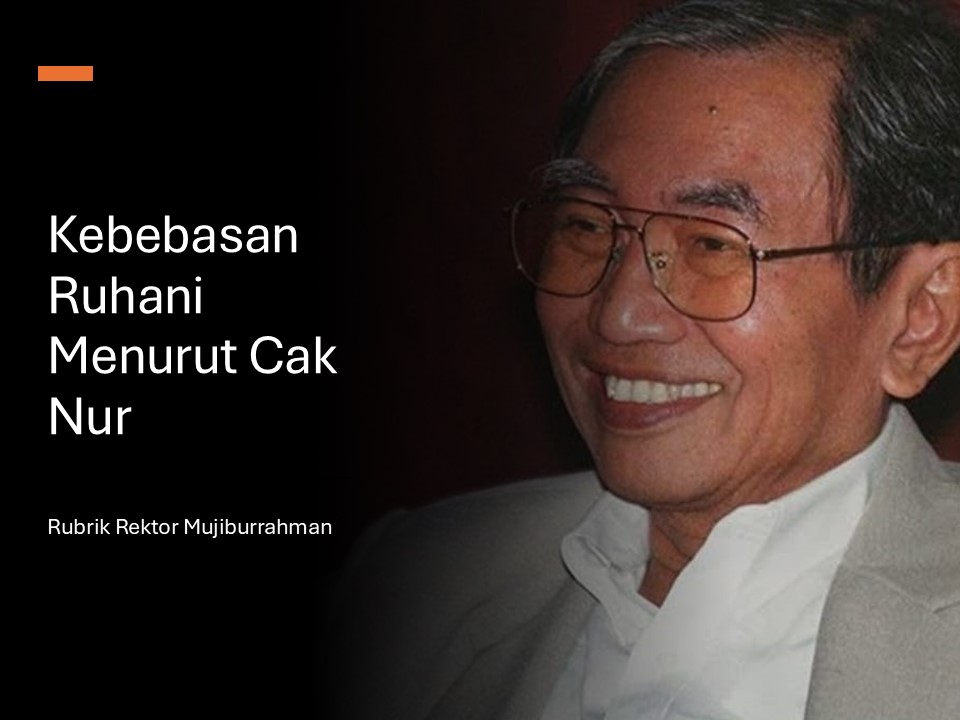
Kebebasan Ruhani Menurut Cak Nur*
Mujiburrahman
PANDANGAN pemikir Muslim, Nurcholish Madjid (1939-2005), yang akrab dipanggil Cak Nur, tentang kebebasan ruhani merupakan konsepsi tentang nilai-nilai Islam sebagai pandangan hidup seorang Muslim. Cak Nur ingin agar Islam bukan sekadar formalitas ritual atau gerakan massa, melainkan nilai-nilai yang merasuk dalam kesadaran tiap pribadi dan menjadi kerangka acuan baginya dalam menjalani hidup. Sumber rujukan utama bagi konsepsinya ini adalah ayat-ayat suci Alqur’an, yang diperkuat oleh hadis-hadis serta penafsiran dan pemikiran ulama klasik hingga modern. Mungkin antara lain karena pengaruh gurunya, Fazlur Rahman (1919-1988), Cak Nur berusaha menggali etika Alqur’an sebagai pedoman hidup manusia. Khusus mengenai konsepsi tentang kebebasan ruhani ini, paling kurang ada tiga tema penting yang kita temukan dalam tulisan-tulisannya, yaitu tauhid, hakikat diri manusia, dan makna dan tujuan hidupnya. Tiga tema ini saling berhubungan satu sama lain sebagai kesatuan yang koheren.
Dalam konsepsi modern, kebebasan biasanya diartikan sebagai kebebasan berpendapat dan berserikat, yang dianggap sebagai hak asasi manusia. Karena pandangan ini pada dasarnya sekuler, maka tidak ada uraian teologis perihal kebebasan ini. Sebagai pemikir Muslim, Cak Nur ingin menegaskan bahwa kebebasan itu berakar pada inti ajaran Islam yang disebut tauhid, yaitu mengesakan Allah, atau keyakinan bahwa tiada tuhan kecuali Allah. Penegasan bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan bermakna bahwa selain Allah tidak boleh dipertuhankan. Kata ‘Allah’ dalam kalimat tauhid, Lâ ilâha illallâh, bagi Cak Nur berarti ‘tiada tuhan selain Tuhan Yang Sebenarnya’ yang dalam terjemahan Inggrisnya, there is no god but God. Bagi Cak Nur, meskipun kita dapat menemukan argumen-argumen rasional dan tekstual tentang keberadaan Tuhan, pada dasarnya kepercayaan akan keberadaan Tuhan itu sudah ada dalam diri kita sejak lahir, yang dalam istilah Islam disebut fitrah. Dengan ungkapan lain, manusia sebenarnya secara alamiah percaya pada keberadaan Tuhan tanpa dalil sekalipun. Karena itu, problem utama yang dihadapi manusia bukanlah ateisme (yang pengikutnya sangat sedikit) melainkan syirk, menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Lawan tauhid adalah syirk yaitu menuhankan sesuatu selain Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
Mengapa tauhid merupakan dasar bagi kebebasan ruhani manusia? Karena ketika manusia hanya mengakui Allah Yang Maha Esa, maka dia hanya akan tunduk dan patuh kepada-Nya. Manusia akan terbebas dari tunduk kepada sesama manusia. Manusia juga tidak boleh merasa lebih tinggi dari manusia lainnya karena semua manusia berasal dari Tuhan yang sama. Manusia adalah setara. Manusia hanya tunduk kepada Allah. Inilah makna generik kata ‘Islâm’ yaitu tunduk dan patuh. Alam semesta juga berislam kepada Allah dalam arti tunduk kepada keteraturan yang dikehendaki-Nya berupa hukum alam, kecuali jika Dia suatu saat menghendakinya lain. Namun, berbeda dengan alam, ruhani manusia diberi Allah kebebasan memilih, antara tunduk atau melawan petunjuk Allah. Ketika manusia dengan sadar memilih untuk mengikuti petunjuk-Nya dan pasrah penuh kepada-Nya, maka pada saat itulah dia mengalami ‘pembebasan ruhani’ karena dia tidak akan tunduk kepada yang lain. Ia tidak tunduk kepada ‘thâghût’, yaitu kekuatan tiranik yang memasung kebebasannya yang hakiki. Ia juga tidak tunduk dalam arti mendewakan kekuatan-kekuatan alam. Ia tidak pula tunduk kepada keinginan-keinginan rendah dirinya atau hawa nafsunya, kepentingan-kepentingan pribadi (vested interests) jangka pendek atau duniawi.
Namun, kebebasan ruhani semacam itu tidaklah mudah diwujudkan. Manusia harus berjuang mewujudkannya. Untuk itu, pertama, manusia harus memahami hakikat dirinya. Cak Nur kemudian mendiskusikan kembali tentang kedudukan manusia sebagai khalifah, dan makna kejatuhan Adam dan Hawa. Ketika Allah mengatakan akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, para malaikat mempertanyakannya karena khawatir manusia akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kekhawatiran melaikat adalah karena manusia memiliki nafsu dan diberi kebebasan memilih. Menurut Cak Nur, mengutip Yusuf Ali, berbeda dengan malaikat, manusia diberi emosi, sebagai kekuatan yang bisa positif, bisa pula negatif. Allah kemudian menunjukkan kepada malaikat keistimewaan Adam, yaitu Allah mengajarinya nama-nama (yakni diberi ilmu pengetahuan). Kisah selanjutnya adalah Adam hidup bersama Hawa di jannah (arti asalnya adalah taman) yang penuh kenikmatan. Tuhan memperingatkan keduanya, agar tidak mendekati pohon (untuk memetik dan memakan buahnya). Kemudian Iblis menggoda keduanya: “Hai Adam, maukah kamu kutunjukkan pohon keabadian dan kerajaan yang takkan punah?” (20:120). Keduanya tergoda, melanggar larangan Tuhan. Adam dan Hawa sadar, lalu bertobat. Tobat mereka diterima, tetapi mereka tetap diperintahkan untuk ‘turun’ ke bumi. Diperingatkan pula, siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan bahagia (tidak takut dan tidak sedih). Jadi, manusia turun ke bumi bukanlah hukuman, tetapi sudah merupakan grand design Allah.
Dari drama Adam-Hawa tersebut tampaklah bahwa, berbeda dengan malaikat, manusia diberi kebebasan memilih antara yang baik dan yang buruk, pahala dan dosa. Dalam dirinya ada nafsu yang dapat membuatnya terjatuh. Nafsu yang paling besar dan berbahaya adalah dua macam, seperti disebutkan dalam rayuan Iblis: keinginan untuk hidup selamanya, dan keinginan untuk berkuasa selamanya. Secara tidak langsung, itu adalah keinginan untuk menjadi ‘Tuhan’. Keinginan untuk hidup selamanya tampak dalam perilaku manusia yang seolah akan hidup selamanya. Dia mengejar kekayaan dan kemewahan hidup tanpa pernah merasa puas. To have more and to use more. Lagi dan lagi. Dia menjadi serakah. Seolah dia tidak akan pernah mati. Begitu pula dengan kekuasaan. Ada yang mengejar kekuasaan demi menumpuk kekayaan. Adapula yang mengejar kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Padahal kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Nafsu rendah ini, yang disebut juga dengan nafsu duniawi, adalah pangkal kejatuhan manusia dari martabat kemanusiaannya sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi.
Karena itu, manusia secara batin harus terbebas dari belenggu nafsu duniawi, kepentingan-kepentingan sempit dan jangka pendek. Untuk itu, manusia harus melakukan pembersihan ruhani, yang dalam hal ini Cak Nur meminjam istilah kaum Sufi: takhalli. Ada potensi baik dan buruk dalam jiwa (nafs) kita. Ada sifat-sifat tercela seperti sombong, rakus, dengki, dendam dan lain-lain, yang bersemayam di jiwa kita. Kita harus bebaskan jiwa kita dari semua sifat ini. Kita melakukannya dengan upaya mujâhadah, melatih pengendalian nafsu. Kita juga melakukannya secara intelektual dengan ijtihad, menggunakan akal pikiran. Bahkan kita juga perlu mengendalikan keinginan-keinginan rendah jiwa itu secara fisik, yang juga disebut jihâd. Perjuangan mengendalikan jiwa ini, dimulai ketika kecenderungan-kecenderungan buruk itu sangat menguasai manusia (ammârah), lalu kemudian ia kadang tunduk kadang melawan (lawwâmah) hingga akhirnya menjadi jiwa yang tenang, terkendali (muthmainnah). Dalam pengertian yang luas, inilah yang disebut taqwa, yaitu kemampuan manusia menjaga dirinya dari kejatuhan moral.
Usaha manusia untuk bebas secara ruhani dari belenggu nafsu angka murka itu juga dibarengi dengan upaya mengisi jiwa dengan kebaikan-kebaikan, yang dalam bahasa Alqur’an disebut ‘amal shâlih, perbuatan baik. Di sinilah Cak Nur menekankan pentingnya penghayatan tentang makna dan tujuan hidup. Cak Nur menegaskan, Islam mengajarkan bahwa manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Tujuan hidup manusia adalah mencapai keredhaan-Nya, yang dalam ungkapan Alqur’an di akhir surah al-Kahfi disebut liqâ’, yaitu bertemu dengan-Nya. Sebagaimana disebutkan oleh ayat tersebut, tujuan hidup manusia adalah bertemu dengan Allah, dan untuk itu, dia harus berbuat baik dan tidak syirik kepada Allah. Dengan demikian, seorang Muslim menemukan makna hidupnya—yaitu bahwa dia merasa hidup yang dijalaninya bernilai—dengan melakukan perbuatan baik (amal saleh) dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, alam lingkungan dan dirinya sendiri. Dalam ungkapan lain, Alqur’an menganjurkan manusia melakukan ihsân, yakni melakukan yang terbaik dalam hidup ini, apapun yang dilakukannya. Wa ahsin kamâ ahsanallâhu ilaika, lakukanlah yang terbaik sebagaimana Allah memberikan yang terbaik bagimu. Yang baik dan terbaik adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat, dan karena itu membahagiakan.
Hidup adalah perjalanan, dan Cak Nur seringkali mengutip berbagai istilah Alqur’an yang menyebutkan jalan seperti sabîl, shirâth, tharîqah, syarîah. Kaum Muslim setiap hari berdoa dalam salatnya, seperti tercantum dalam al-Fatihah, agar diberi pentujuk mengikuti jalan yang lurus, jalan yang benar, yang menuju kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa konsistensi dalam kebaikan itu tidaklah mudah. Manusia harus terus-menerus berusaha dan memohon pentunjuk-Nya. Apalagi tiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga jalan hidup yang dijalani juga berbeda-beda. Karena itu, masing-masing kita akan menjalani jalan yang tidak persis sama, meskipun tujuan akhirnya adalah sama. Selain itu, karena tujuan akhir adalah Tuhan, dan Tuhan itu transenden, melampaui segala sesuatu, maka pada hakikatnya manusia tidak akan pernah benar-benar sampai kepada-Nya. Manusia hanya mungkin mendekati-Nya, bertaqarrub kepada-Nya. Karena itu, tiap orang harus rendah hati, tidak boleh merasa telah mencapai kemutlakan sehingga tidak lagi mau mendengarkan orang lain. Hal ini menurut Cak Nur disimbolkan oleh pernyataan dalam Alqur’an bahwa air yang diminum di surga kelak adalah salsabîla. Menurut sebagian mufassir, salsabîla itu terdiri dari dua kata, yaitu sal dan sabîla yang artinya ‘tanyakanlah jalan’. Kita akan terus bertanya tentang jalan yang kita lewati menuju Allah, karena jalan itu tanpa batas.
Demikianlah, kebebasan ruhani dalam konsepsi Cak Nur sangat Sufistik, dan tidak mudah diraih. Ia menuntut perjuangan terus-menerus. Namun, justru di situlah letak perjuangan manusia dalam menggapai makna dan tujuan hidupnya. Bagi Cak Nur, jika manusia sudah terbebas secara ruhani, maka dia akan dapat membebaskan dirinya dari apapun yang menggoda atau menghalanginya di alam nyata. Sebaliknya, seorang yang secara sosial mengaku ingin membebaskan masyarakat dari belenggu korupsi, kebodohan dan kemiskinan, sementara dirinya sendiri belum terbebas dari cengkeraman hawa nafsu, maka dia akan gagal atau mengkhianati perjuangannya itu sendiri. Wallâhua’lam.
* Essai ini pernah didiskusikan secara daring dalam kegiatan ‘Pekan Cak Nur’ menjelang Haul Cak Nur ke-16 yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS) Jakarta, pada 28 Agustus 2021.