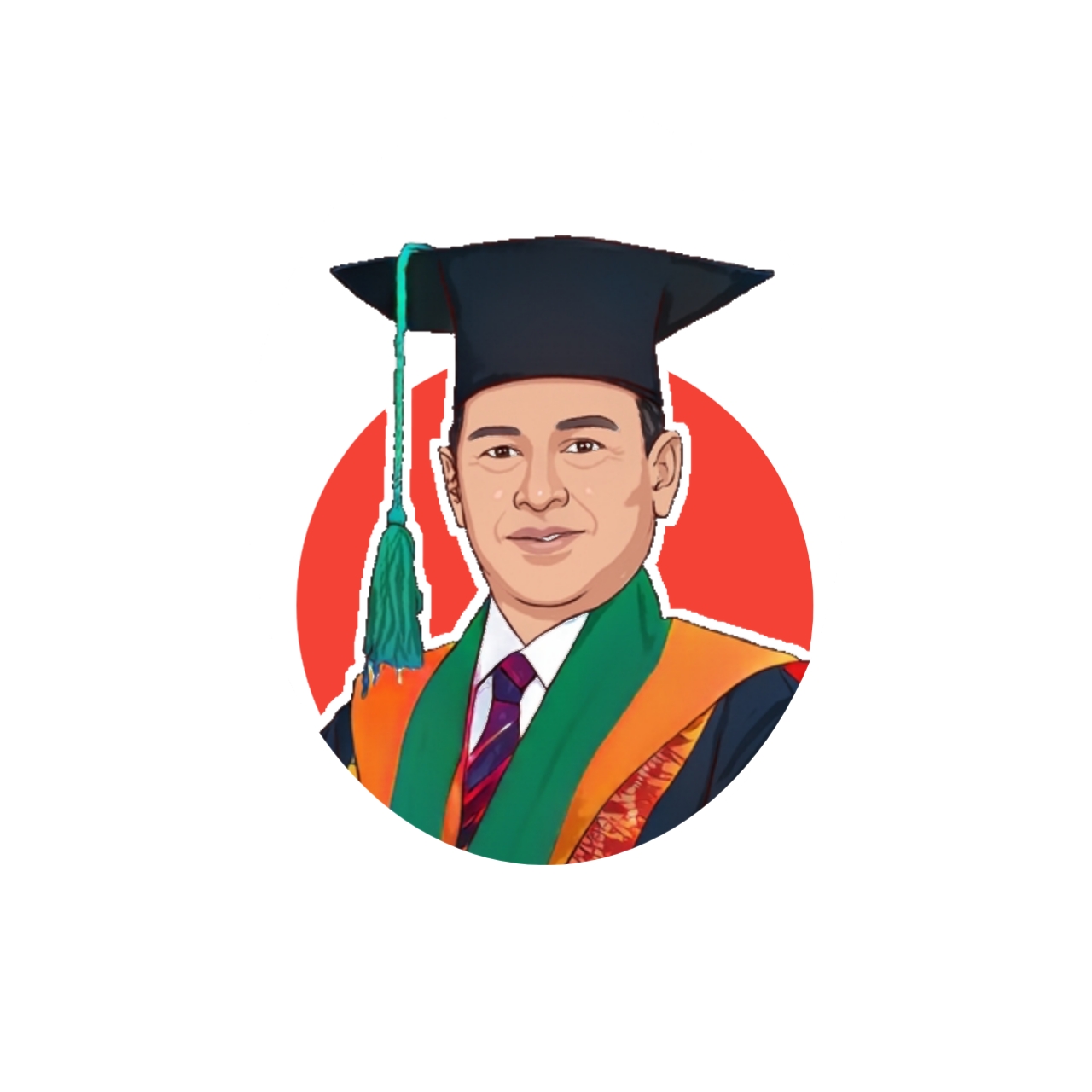
Haji sebagai Perjalanan Air Mata? (Catatan tentang Spiritualitas Al-Qur’an)
Oleh: Wardani
Pendahuluan
Haji adalah salah satu dari rukun Islam. Berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain, haji merupakan puncak dari ajaran dalam Islam. Mengapa disebut demikian? Hal itu karena, tidak hanya dilihat dari urutannya sebagai rukun ke-5, yaitu rukun terakhir dalam Islam, melainkan juga karena haji memerlukan pengetahuan yang menyeluruh tentang rangkaian ibadah ini, pelaksanaan yang ekstra menguras tenaga dan pikiran, kesungguhan yang melibatkan curahan tenaga fisik dan penghayatan batin maksimal, dilaksanakan dalam waktu cukup lama, memerlukan persiapan, baik dari kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan finansial untuk keberangkatan dan akomodasi di Tanah Suci. Bahkan, tidak hanya itu, untuk melaksanakan haji, calon jemaah perlu menunggu waktu giliran keberangkatannya beberapa tahun lamanya.
Meskipun haji adalah ibadah yang berat dilaksanakan dan telah dipersiapkan dengan baik, tidak jarang bahwa kaum muslimin belum memahami pesan sentralnya, yaitu pesan inti yang menjadi muara dari seluruh pelaksanaan haji. Pesan sentral ini berisi inti ajaran Islam yang menghubungkannya secara koheren dengan ajaran-ajaran pokok Islam, seperti mencetak muslim yang bertakwa (muttaqī). Takwa ini adalah tujuan sentral seluruh ajaran al-Qur`an. Bahkan, semua ajaran Islam, baik shalat, puasa, dan membayar zakat, pada prinsipnya, bermuara pada tujuan sentralnya, yaitu ketakwaan. Takwa tidak hanya berisi pelaksanaan perintah Allah swt dan menghindari larangan-larang-Nya secara ritualistik-formal. Hal itu karena dalam Islam, ada dimensi luar (ibadah formal), juga ada penghayatan batin di dalamnya.
Dimensi ketakwaan dalam haji seharusnya menjadi muara pelaksanaan ibadah. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya, tak jarang ibadah yang sakral ini dilaksanakan bukan didasarkan atas peningkatan ketakwaan, melainkan karena tujuan-tujuan lain yang tidak menjadi tujuan utamanya. “Penyimpangan” dari pesan sentral ini pernah diingatkan dalam riwayat berikut:
Diriwayatkan dari al-Khathīb al-Baghdādī dari Anas RA, Rasulullāh SAW bersabda, “Suatu masa akan datang di mana orang kaya di zaman itu berhaji untuk tamasya, kelompok yang menengahnya berhaji untuk berbisnis, kebanyakan mereka berhaji untuk riyā dan sum’ah, dan orang-orang fakirnya berhaji untuk mengemis.”
Di era sekarang, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya animo kaum muslimin, jumlah kaum muslimin yang berhaji dan berumrah dari tahun ke tahun semakin banyak, baik untuk haji wajib maupun haji sunnat. Sebagian dari mereka dengan ketulusan hati melaksanakan ibadah ini untuk mendekatkan diri kepada Pencipta. Namun, di sisi lain, berbagai tujuan lain, seperti untuk kepentingan peleseran, untuk menunjukkan status sosial di masyarakat melalui media sosial, dan tentu saja jua untuk kepentingan bisnis, juga ditemukan. Fenomena di kalangan pesohor Negeri ini, seperti kalangan artis, misalnya, tidak segan memposting perjalanan haji atau umrah mereka – entah dengan tujuan dakwah atau narsisme – melalui media sosial. Sekarang, apa yang disebut sebagai “agama yang online” (online religion) menjadi trend di kalangan banyak orang yang sedang melaksanakan ibadah. Foto dan video, bahkan siaran langsung (streaming video), tak ayal dibagikan melalui saluran seperti Facebook. Baik online religion sebagai berbagi informasi kegaiatan ibadah yang dilaksanakan maupun religion online sebagai media pengajaran agama secara online, sama-sama ada plus dan minusnya. Akibatnya, tidak ada batas privasi, di mana aktivitas individual dishare secara luas dan diketahui oleh ribuan bahkan jutaan pasang mata yang siap setiap saat menegok dunia maya. Ada suka (like) dan ada juga ketidaksukaan (dislike). Di sisi lain, sebagian pengamat mengapreasiasi model pengetahuan tentang agama yang disebarkan secara online sebagai model demokratis pengajaran agama, di mana para netizen atau orang melihatnya (viewer) bebas menilai, bahkan mengomentarinya. Di sisi lain juga, dari perspektif agama, ibadah sebagai pengalaman individual menjadi terumbar, rentan akan narsisme, pamer, riyā`, dan sum’ah.
Spiritualitas
Spiritualitas terambil dari kata “spirit” (semangat, roh, inti). Konon, kata “spirit” terambil dari kata “spiritus” yang bermakna “nafas kehidupan” yang meski tidak terlihat, namun memberikan “energi” bagi hidup kita dan dengannya hidup dianggap bermakna. Dualitas (bukan dualisme) ajaran ini sudah dikenal dalam Islam. Dalam literatur Islam klasik, dimensi ini sering disebut dengan lub (jamaknya: albāb, isi) yang bermakna “inti” atau dimensi batin/dalam, sedangkan dimensi zahir/luar disebut qisyr (jamaknya: qusyūr, kulit). Dalam kajian al-Qur`an, selain istilah dualitas “ẓāhir-bāṭin” (terkadang secara lahiriah disebut “ẓahr-baṭn” [punggung-perut] untuk dimensi yang tampak dan yang tersebumnyi), juga dikenal istilah “ḥadd-maṭla’” (secara harpiah: “batas-tempat terbit”, secara terminologis: “aturan formal-sumber/dasar”). Dalam kajian tashawwuf, dualitas ini sudah dikenal dengan “syarī’ah-ḥaqīqah”. Juga dikenal istilah lain, “bentuk-isi” (forma-esensi, form-essence), dan sebagai kecenderungan kuat keduanya, “formalisme-esensialisme”. Istilah terakhir ini bermuara dari pembedaan filsafat antara “aksiden-substansi/esensi” (arḍ-jawhar).
Ibadah terdiri dari dimensi formal dan dimensi esensial. Dimensi formal adalah amaliyah ritual yang disyariatkan dalam Islam, seperti shalat dan berpuasa pada bulan Ramadhan.
1. Spiritualitas: kebajikan (al-birr), kebenaran (shidq), dan ketakwaan (taqwā)
Allah SWT berfirman dalam Q.s. al-Baqarah: 177:
لَيْسَ الْبِرَّاَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفىِ الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِۗ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗوَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ
Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
Dalam ayat di atas, disebutkan adanya dua macam aspek dalam beragama, yaitu:
Pertama, aspek formal, yaitu yang disimbolisasikan di sini dengan menghadapkan wajah ke ke timur atau ke barat. Menurut al-Wāḥidī, sebagaimana dikutip oleh Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, ayat ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan seseorang kepada Nabi Muḥammad tentang apakah jika seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat Syahādah, lalu melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam, ia pasti masuk surga. Turunnya ayat ini tampak menjadi jawaban bahwa keimanan dan pelaksanaan ibadah saja, tanpa dibarengi oleh pelaksanaan kewajiban-kewajiban lain, termasuk ibadah sosial dan kualitas kepribadian baik, seperti kesabaran dan kejujuran, tidak mencapai tingkat kebajikan (al-birr). Namun, uniknya, ayat ini bahkan tidak berbicara tentang balasan dengan surga dimaksud, melainkan sejauh mana dulu capaian orang yang beriman, yaitu target kebajikan itu. Memang, tujuan orang beragama adalah ketakwaan dan ridha Allah swt, jadi (ridha) Tuhan sebagai “tujuan”, sedangkan surga adalah “efek” dari ridha-Nya. Bahkan, di beberapa ayat lain dalam al-Qur`an, “ridha Allah yang melimpah adalah justeru lebih bermakna/agung” (wa riḍwānun min Allāh akbar). Ayat ini memang mengarahkan dari perspektif uslūb al-ḥakīm (gaya bahasa Tuhan yang Maha-bijaksana dengan mengalihkan jawaban dari pertanyaan awal ke hal lain yang lebih penting) ke tujuan yang lebih esensial, menyentuh kesadaran terdalam dalam beragam, dan inherent dalam jiwa.
Riwayat lain menyebutkan perbedaan penganut agama lain soal arah menghadap ketika beribadah; umat Yahudi ke barat, sedangkan umat Nashrani ke timur. Oleh karena, al-Zamakhsyarī, sebagaimana dikutip oleh Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, menyebutkan bahwa sebelum turunnya ayat ini, kaum muslimin dan kalangan Ahl al-Kitāb terlibat dalam perdebatan soal kiblat. Sebagaimana riwayat di atas, riwayat ini juga sebenarnya sama-sama menegaskan hal yang sama, yaitu soal formalisme dalam beragama, termasuk dalam hal ini, adalah menghadap timur atau barat. Tentu saja, menghadap kiblat merupakan persoalan yang penting, karena tanpanya, shalat menjadi tidak sah. Namun, ada hal esensial yang tidak boleh dilupakan, yaitu ketakwaan sebagai jiwa atau muara seluruh ibadah. Semua ibadah bertujuan mencetak seorang muslim untuk menjadi orang yang bertakwa.
Kedua, dimensi esensial/spiritual yang harus diwujudkan adalah dalam bentuk: (1) keimanan, yaitu beriman dengan Allah SWT, hari kiamat, malaikat, kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT, dan para Nabi (selengkapnya: iman dengan Nabi-Nya, dan ketentuan/takdir-Nya); (2) berbuat baik kepada sesama, yaitu: memberikan harta yang masih disayangi kepada kalangan kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibn sabīl, peminta-minta, dan budak; (3) mendirikan shalat dan menunaikan zakat; (4) menepati janji jika berjanji dan bersabar menghadapi penderitaan. Empat hal ini sebenarnya merepresentasikan: keimanan, berbuat kebaikan, menunaikan ritual pokok dalam Islam, dan kepribadian. Empat hal inilah yang menjadi bukti “benarnya” iman seseorang (shidq) dan sekaligus menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa.
2. Spiritualitas: merasakan kebesaran Allah swt dan berbuat baik (iḥsān) sebagai representasi takwa (Q.s. al-Hajj: 37)
لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاۤؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْۗ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ
Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muḥsin.
Seperti halnya Q.s. al-Baqarah: 177, ayat ini memuat dua hal, yaitu: aspek formal ajaran berupa pelaksanaan ritual qurbān yang disimbolisasikan di sini dengan daging dan darah hewan dan aspek esensial/spiritual yang merupakan inti ibadah qurbān ini berupa ketakwaaan. Ayat di atas menuntun kita dalam menangkap salah satu dimensi spiritualitas itu dengan menanamkan kesadaran dalam batin tentang kekuasaan Allah swt yang telah “menundukkan” (sakhkhara, taskhīr) hewan-hewan yang akan diqurbānkan itu “untuk kalian” (sakhkhara lakum), untuk kita, sebagai sarana ibadah. Alam semesta ini bisa menjadi “liar” alias “tak terkendali” jika Dia tidak mengendalikannya, seperti matahari dan bulan (Q.s. al-Ra’d: 2, Ibrāhīm: 33, al-‘Ankabūt: 61, Luqmān: 29, Fāṭir: 13), malam dan siang (Q.s. Ibrāhīm: 32, al-Zumar: 5), bintang-bintang (Q.s. al-Naḥl: 12), laut (Q.s. al-Naḥl: 14, al-Jatsiyah: 12), gunung (Q.s. Ṣād: 18), angin (Q.s. al-Anbiyā`: 79, Q.s. Ṣād: 36), bahkan semua apa yang ada di bumi dan di langit (Q.s. al-Ḥajj: 65, al-Jātsiyah: 13) sehingga segala fasilitas yang mungkin digunakan oleh manusia bisa dinikmati secara sempurna (Q.s. Luqmān: 20), termasuk hewan-hewan, seperti burung (Q.s. Ṣād: 19). Ditundukkannya hewan ternak, seperti digunakan sebagai tunggangan (alat transportasi) disebut secara khusus dalam Q.s. al-Zukhruf: 13. Dalam ayat ini, sebagaimana juga tampak dalam ayat di atas, konteksnya adalah agar manusia bisa mengingat nikmat Allah swt., lalu merasakan kebesaran-Nya.
Di samping dengan menyadari bahwa semua hal ini, termasuk hewan sembelihan qurbān, bisa dinikmati atau dimanfaatkan karena ditundukkan oleh Tuhan, kebesaran-Nya juga bisa dirasakan jika manusia menyadari bahwa Allah swt telah memberi petunjuk (disebut dalam ayat: ‘alā mā hadākum). Konteksnya dengan penyembelihan hewan qurbān ini adalah karena Allah swt memberikan petunjuk-Nya kepada manusia agar hewan tersebut, sebagai sarana/fasilitas yang diciptakan dan ditundukkan oleh-Nya, disadari sebagai makhluk-Nya, dan manusia sebagai penikmatnya. Pemaknaan seperti ini tidaklah secara otomatis disadari oleh manusia yang dilalaikan oleh rutinitas, karena hal ini bisa saja dianggap sebagai hal yang biasa, keseharian, profand. Lalu, dengan begitu, kita sering tidak menyadari yang sakral (sacred), yaitu andil Tuhan, di baliknya. Hidayah/petunjuk bukanlah hal mudah didapatkan. Oleh karena itu, dalam al-Qur`an, petunjuk Tuhan disebut sebagai nikmat (Q.s. al-Fātiḥah: 6-7). Betapa banyak orang yang telah tersesat dari jalan yang benar dalam beragama. Betapa banyak juga orang yang berupaya mencari kebenaran dalam agama, namun tidak menemukannya. Sebagian dari mereka jatuh dalam penyembahan yang sebenarnya merupakan makhluk Tuhan, seperti matahari dan hewan. Dalam hal ini, spiritualitas dalam ayat di atas menekankan tawḥīd dan pengagungan-Nya (takbīr). Dari redaksi ayat di atas (Q.s. al-Ḥajj: 37), tampak bahwa memang dua aspek yang seharusnya menyatu ini tidak secara otomatis menjadi kesadaran seorang muslim, sehingga seorang muslim harus berupaya meraih keduanya.
Q.s. al-Baqarah: 177 tampak berkaitan dengan Q.s. al-Baqarah: 189 berikut:
يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰىۚ وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit.52) Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
Dalam ayat ini, persoalan tentang kebajikan (al-birr) dan kaitannya dengan takwa juga disinggung. Ayat ini disebutkan dilatarbelakangi oleh kebiasaan keliru di kalangan masyarakat Arab ketika mereka pulang ke rumah sehabis menunaikan ibadah haji. Mereka tidak masuk rumah melalui pintu depan, melainkan melalui pintu belakang. Ayat ini membantah kebiasaan itu sebagai bagian dari kebajikan (al-birr). Sembari menyerukan bahwa memasuki rumah memang seharusnya lewat pintu (depan)-nya (di sini mengembalikan ke kondisi normal berdasarkan kebiasaan dan seharusnya), ayat ini juga menegaskan hal yang paling esensi (di sini al-Qur`an, mengisi hal yang biasa itu dengan esensi), yaitu bahwa kebajikan itu seharusnya bermuara dari ketakwaan, karena memasuki rumah melalui pintu belakang tidak ada kaitannya sama sekali dengan ketakwaan.
Spiritualitas Haji
1. Al-Ḥajj al-mabrūr (haji yang diterima): benar niat dan pelaksanaannya, serta berefek kebajikan (al-birr)
Sebutan “haji mabrūr” tampak sangat dekat konotasinya dengan ide kebajikan (al-birr) yang karakteristiknya disebutkan disebut dalam Q.s. al-Baqarah: 177 di atas.
1. Kesadaran batin akan ridha Allah SWT sebagai tujuan
a. Al-Baqarah: 197
وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۗ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ࣖ
Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu’), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya.
b. Āl ‘Imrān: 98
فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ەۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ
Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.
2. Haji menjadi sarana membekali diri dengan ketakwaan
Q.s. al-Baqarah: 197:
اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ
(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafats, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.
Perintah untuk mengisi rangkaian-rangkaian ibadah haji dengan spirit ketakwaan juga sebelumnya ditegaskan di ujung ayat 196 dari sūrah ini, dengan ungkapan “dan bertakwalah kepada Allah” (wattaqū Allāh). Akhir ayat ini ditutup dengan seruan ketakwaan itu kepada ulū al-albāb. Menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, dalam tafsirnya, istilah ini bermakna “orang-orang yang memiliki akal pikirian” (aṣḥāb al-‘uqūl). Menurutnya, penggunaan sebutan ini bertujuan agar kaum muslimin menggunakan akal pikiran dalam memahami perintah Allah berkaitan dengan haji dan tahapan-tahapannya.
3. Haji: sarana memaksimalkan mengingat Allah swt, melebihi segalanya
Pesan spiritualitas ini disebutkan dalam Q.s. al-Baqarah: 200:
فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۤءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
Apabila kamu telah menyelesaikan manasik (rangkaian ibadah) haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,” sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun.
Menurut riwayat Mujāhid, bangsa Arab memiliki kebiasaan sejak masa Jahiliyyah membangga-banggakan nenek-moyang mereka, dengan menyebut-nyebut nama mereka. Ayat ini berisi perintah untuk mengganti kebiasaan itu dengan mengingat Allah swt. Menurut riwayat lain, bangsa Arab ketika melaksanakan ibadah haji, berdoa agar mereka diberikan kekayaan, diberikan onta, meminta diturunkan hujan, keturunan, dan sebagainya. Semuanya hanya permintaan kebahagiaan di dunia, tapi mereka tidak berdoa untuk kepentingan kebahagiaan di akherat.
Penutup
Selain tiga aspek utama dimensi spiritualitas haji, ada beberapa aspek lain, yang semua bermuara pada penguatan dimensi keberagamaan yang inherent dalam jiwa, bertujuan mendekatkan diri dengan Allah SWT, menggalakkan ketakwaan, dan mengingat-Nya di setiap momen. Semua dimensi spiritualitas ini mengokohkan orang yang berhaji sebagai pribadi muslim yang komplit; tidak hanya dibekali pelaksanaan formal rangkaian ibadah-ibadah, melainkan ibadah sosial dan keperibadian yang tabah dan jujur. Semoga momen haji ini membekas dalam jiwa para haji sehingga bisa mencetak mereka sebagai pribadi yang takwa. Jika nilai-nilai intrinsik ini dihayati dan diiternalisasikan dalam diri seorang muslim, ia merasakan kehadiran Tuhan di setiap saat dan di setiap tempat. Mungkin saja, rangkaian ibadah ini disertai dengan uraian air mata, akhirnya, meminjam kata-kata Taufik Ismail, haji menjadi “perjalanan air mata”, tepatnya “air mata spiritual”, atau lebih tepatnya lagi “perjalanan spiritual”, karena semua ibadah menyentuh dimensi terdalam dalam lubuk jiwa. Karena spiritualitas haji memanjang dari momen berhaji ke momen sesudahnya, maka perjalanan itu tetap berjalan.
Tag:Haji, Opini Dosen, Wardani



