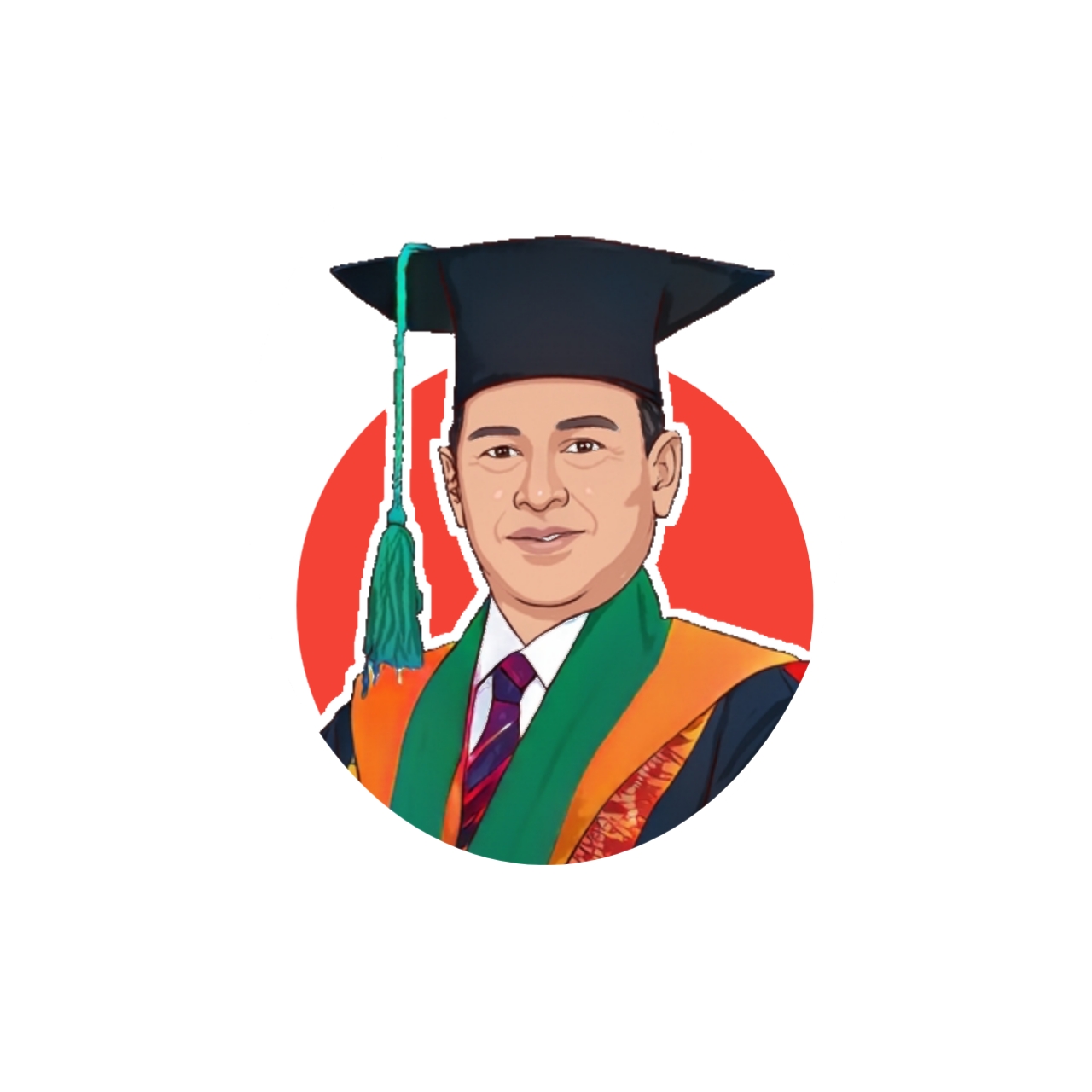
Puasa sebagai Pengendalian Diri
Puasa sebagai Pengendalian Diri
Penulis: Prof. Dr. H. Wardani, M.Ag.
(Guru Besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin)
Editor: Noor Hasanah, M.A.
Ramadhan tiba. Suka-cita masyarakat menyambut bulan ini diekspresikan di mana-mana; lewat ucapan “Selamat berpuasa”, “Ramadhān mubārak”, “Ramadhān karīm”, dan sebagainya. Kita kini berpuasa; dari anak kecil sekelas SD hingga orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Alhasil, puasa sudah biasa kita lakukan, layaknya seperti siklus tahunan saja, berulang dan berulang lagi, seakan jadi rutinitas saja. Namun, dalam pelaksanaannya, tak jarang kita temukan, orang yang sedang berpuasa melakukan hal-hal di luar tindakan bermoral, seperti kebut-kebutan habis berbuka, atau menjelang buka puasa. Ada juga orang yang berpuasa, ketika berbuka puasa, terlalu banyak hidangan yang terkesan berlebihan, serta makan secara berlebihan; tidak hanya jenis makanannya, melainkan juga makannya overload alias terlalu kenyang. Banyak orang yang berpuasa, namun tidak banyak mengetahui hakikatnya. Lalu apa hakikat berpuasa itu?
Pengertian
Secara kebahasaan, puasa dalam bahasa disebut “shaum” atau “shiyām”, bermakna “menahan” (al-imsāk). Pengertian secara kebahasaan ini, pernah digunakan oleh al-Qur`an dalam pengertian menahan untuk berbicara. Lalu, secara agama (Islam), puasa diartikan sebagai menahan dengan niat mendekatkan diri dengan Allah Swt, dari makan, minum, dan hal-hal lain membatalkan, seperti berhubungan suami-istri, dari terbit fajar kedua hingga matahari terbenam.
Makna “menahan” itu sebenarnya berisi “pengendalian”, atau dalam istilah tashawwuf, sering disebut dengan “perjuangan mengendalikan nafsu” (mujāhadat al-nafs), atau dalam ungkapan lain, “kontrol diri” (self-control). Namun, bedanya adalah bahwa self-control adalah pengendalian diri secara psikologi agar seseorang tetap teratur, terbimbing, dan terarah dalam tindakannya menuju hal yang positif. Fokusnya adalah pengendalian emosi, sehingga tenang dalam menghadapi situasi panik. Sedangkan, istilah “pengendalian diri” di sini dimaksudkan lebih spesifik, yaitu dalam pengertian agama (Islam) berkaitan dengan pengendalian hawa nafsu agar tetap pada rel tuntunan Islam, tidak hanya pengendalian emosi, melainkan semua yang terkait dengan diri, seperti harta kekayaan, rasa takut, sikap hidup yang hedonis dan materialistis.
Pengendalian diri adalah bagian penting dari hakikat beragama. Dalam Islam, ada aturan, lalu para pemeluknya diperintahkan untuk “mengendalikan diri” agar sesuai dengan aturan itu. Islam, bahkan semua agama, berupaya menciptakan tatanan. Dalam Islam, ada perintah dan larangan, bahkan ada yang dibolehkan (mubāh). Semuanya berisi pengendalian. Dalam hal yang diperintahkan, maka orang yang beriman diperintahkan untuk “mengendalikan diri”, baik dalam pengertian menyiapkan diri, berkomitmen, dan disiplin melaksanakannya. Ajaran shalat, misalnya, berisi perintah pengendalian diri, karena orang yang mengerjakan, harus siap, mengalokasikan waktu, dan untuk mengabaikan hal lain dulu demi melaksanakan shalat. Begitu juga, dalam larangan, bahkan tentu ada ajaran Islam tentang pengendalian diri, terutama untuk tidak melanggar. Bahkan, dalam hal-hal yang dibolehkan (mubāh), juga ada pengendalian diri. Itulah sebab dalam puasa, dilarang makan dan minum, meskipun terhadap hak miliknya sendiri. Begitu juga, dilarang menggauli meski terhadap pasangan sendiri, selama berpuasa.
Mengapa terhadap hal-hal yang mubāh juga perlu pengendalian? Karena jika tidak ada batasan, manusia akan berlebihan yang dalam bahasa agama, disebut tabdzīr (membuang-buang, boros) atau isrāf (berlebihan). Sesuatu yang berlebihan, tentu akan menjadi tidak baik, karena hal itu terkait dengan pengendalian jiwa, meski terhadap yang mubāh. Bahkan, menurut al-Syāthibī, seorang ahli Ushūl al-Fiqh beraliran Mālikiyyah yang dalam beberapa hal dari pemikirannya mengritik terhadap, namun juga terpengaruh oleh ajaran tashawwuf, melalui karyanya, al-Muwāfaqāt, sebenarnya tidak mubāh dalam pengertian sama sekali netral, melainkan ia akan bernilai dianjurkan atau tidak. Bukti bahwa yang dianggap mubāh tidak selalu bersifat netral adalah sabda Nabi Muhammad saw bahwa menggauli istri yang sah adalah berpahala, lantas kemudian menimbulkan kebingungan para sahabat, lalu mereka menanyakan kebenaran hal itu. Nabi lalu menjawab dengan mengajak beranalogi kebalikannya (mafhūm al-mukhālafah) dengan balik bertanya, “Jika hubungan seksual itu dilakukan terhadap wanita bukan pasangan sahnya, apakah berdosa?”. Sontak para sahabat menjawab, “Tentu saja!”. Nabi kembali menjawab bahwa begitu juga, jika dilakukan terhadap pasangan sahnya (istri), maka berpahala. Di sini, apa yang dianggap mubāh sebenarnya memiliki nilai (pahala). Maka dalam puasa, yang mubāh itu pun harus dikendalikan penggunaannya. Nah, moment puasa sesungguhnya adalah momentum pembiasaan (ta’wīd, habituation) untuk pengendalian, karena pengendalian itu menjadi bagian inti dari keberagamaan. Mengapa disebut momentum pembiasaan? Karena hanya berlangsung selama sebulan (Ramadhān), sebagai momen pendidikan, yang seharusnya “inti pengendalian” itu dalam banyak hal dari beragama diterapkan di bulan-bulan lain.
Keterkaitan Puasa dengan Iman dan Takwa, dan Hubungannya dengan Umat Terdahulu
Jika dilihat dari keterkaitan puasa dengan ajaran-ajaran lain dalam Islam secara integral, maka ajaran puasa sebagai pengendalian diri terhubung dengan tiga poros yang disebut dalam Q.S. al-Baqarah: 183 yang berisi perintah kewajiban berpuasa: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa”. Sebagaimana tampak dalam ayat tersebut, tiga poros itu adalah sebagai berikut. Pertama, iman, karena ayat ini diawali dengan “wahai orang-orang yang beriman”. Itu artinya, puasa adalah realisasi atau implementasi dari komitmen orang-orang beriman. Berpuasa menjadi bagian dari pelaksanaan dari iman. Orang yang beriman wajib berpuasa. Lalu, di mana benang-merah dari ajaran pengendalian diri dengan iman? Jelas sekali! Karena beriman bermakna secara tawhidi adalah penafian (nafy) segala yang dianggap sebagai tuhan, selain Allah Swt. dan bersaksi mengakui (itsbāt) bahwa Dia-lah yang berhak diakui sebagai Tuhan dan yang berhak untuk disembah. Beriman kepada Allah Swt memiliki pengertian “menutup” pintu bagi ketuhanan yang selain dari Dia. Pengendalian sealur dengan penafian, yaitu terhadap hal-hal selain Dia sebagai Tuhan sejati. Oleh karena itu, syirik dilarang. Di samping itu, iman juga memang berimplikasi pada pengendalian diri dalam ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang.
Kedua, takwa, sebagaimana disebutkan dalam potongan akhir ayat, “… semoga kalian bertakwa”. Takwa adalah realisasi dari komitmen beriman, dan keduanya sama-sama berisi inti pengendalian diri, sehingga iman, takwa, dan puasa adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa Tuhan menggunakan kata “semoga” (la’alla), padahal sebagai Tuhan, Allah Swt tidak perlu “berharap”, karena semuanya bisa diwujudkan-Nya hanya dengan kun, “jadilah”, maka akan jadi? Dalam bahasan ‘Ulūm al-Qur`ān, umumnya dijelaskan bahwa kata ini menunjukkan adanya sesuatu yang kemungkinan besar akan terwujud (al-tawaqqu’) (al-Suyūthī, al-Itqān juz I: 173). Itu artinya, puasa adalah sebuah sarana yang menjadi niscaya dalam mewujudkan ketakwaan, meskipun puasa tidak menjadi indikator satu-satunya ketakwaan. Jadi, dalam hal ini, Tuhan “berharap” (dalam pengertian memerintahkan) agar orang-orang yang beriman dapat mewujudkan ketakwaan melalui berpuasa. Maka dalam hal ini, orang-orang yang berimanlah sebagai hamba yang bertanggungjawab dan diberikan kebebasan–yang karenanya nanti di akhirat, mereka akan diberi ganjaran–untuk mewujudkannya (ketakwaan). Selanjutnya, kaitan antara puasa dan takwa adalah takwa menjadi muara atau tujuan berpuasa; kedua, ketakwaan harus menjadi spirit berpuasa. Maka pengendalian diri sebenarnya adalah sebuah totalitas; tidak hanya berpuasa secara fisik dengan menahan dari makan dan minum, melainkan juga semua sifat dan perilaku tidak terpuji. Sama halnya dengan berkurban, di mana al-Qur`an menyinggung bahwa bukan daging atau darahnya yang sampaikan kepada Tuhan, melainkan ketakwaan.
Ketiga, ajaran umat terdahulu. Puasa adalah sebuah ibadah yang tidak hanya diwajibkan kepada umat Islam sekarang ini, melainkan kepada orang-orang sebelum mereka. Puasa menjadi syariat yang menghubungkan antara umat ini dengan umat terdahulu. Ajaran tentang puasa menjadi ajaran yang ditekankan di setiap umat Islam, bahkan di setiap agama. Itu artinya, puasa adalah ajaran yang sangat penting, karena berisi pendidikan tentang pengendalian diri. Hanya saja, praktik dan batasannya yang berbeda. Dalam syariat kita, puasa adalah menahan diri dari semua yang dianggap bisa membatalkan, seperti makan dan minum, dalam waktu yang ditentukan, sejak fajar hingga matahari terbenam. Setelah itu, di malam hari, semua yang dilarang ketika berpuasa di siang hari, menjadi boleh. Dalam al-Qur`an (Q.S. al-Baqarah: 187) sendiri disebutkan, kebolehan bercengkerama dengan istri (rafats), menggauli, serta makan dan minum hingga waktu fajar yang disimbolkan dengan perpindahan dari ‘benang hitam’ (gelapnya malam) ke ‘benang putih’ (terangnya siang).
Puasa Diwajibkan (Kutiba) sebagai Pengendalian Diri dan Benang Merahnya dengan Kewajiban Lain
Penekanan akan pentingnya ajaran puasa sebagai kewajiban dan sebagai bagian dari ketakwaan diungkapkan dengan “ditulis” (kutiba), yang kemudian diterjemahkan dengan “diwajibkan”. Semula akar kata kaf-ta-ba (كتب) semula berarti mengumpulkan sesuatu ke sesuatu. Kemudian, kata berkembang dengan makna “kewajiban” (Q.S. al-Baqarah: 183), dan kata kitāb bermakna “hukum/aturan” (Ibn Fāris, Mu’jam Maqāyīs al-Lughah V: 158-159).
Menarik untuk diamati bahwa Q.s. al-Baqarah: 183 yang berisi perintah berpuasa berada dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya yang juga menggunakan redaksi “ditulis” (kutiba), kemudian di ujung masing-masing ayat dikaitkan dengan indikator ketakwaan, yaitu (1) perintah menegakkan hukum qishāsh, yaitu hukuman setimpal atas perbuatan jahat yang dilakukan pada kasus pembunuhan (2: 178), diakhiri (2: 179) dengan pernyataan bahwa dalam qishāsh adalah kehidupan yang perlu direnungi oleh orang-orang yang berakal (ulū al-albāb), sehingga dengan demikian diharapkan terwujud ketakwaan; (2) perintah kepada orang yang akan meninggal untuk berwasiat dari hartanya untuk diberikan kepada kedua orang tua dan kerabat dekatnya, di mana wasiat itu dianggap sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (2: 180); dalam hukum waris, pembagian harta seperti ini kemudian dirinci dalam hukum pembagian waris; (3) perintah berpuasa (2: 183) yang diakhiri dengan harapan agar puasa itu menjadi sarana mencetak pribadi mukmin yang bertakwa. Harapan dengan melakukan hal itu dikaitkan dengan ketakwaan disebutkan dua kali, yaitu pada perintah qishāsh dan perintah berpuasa, dan satu kali diungkapkan dengan “sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”, dalam kasus perintah berwasiat. Di samping itu, di tempat lain dalam al-Qur`an, kata kutiba juga digunakan, namun kali ini dalam kaitannya dengan kewajiban berjihad (berperang) melawan orang-orang kafir yang ketika menindas kaum muslimin (Q.S. al-Baqarah: 216).
Terdapat pola yang sama antara kasus-kasus kewajiban yang telah disebutkan di atas (berpuasa, berwasiat, menegakkan qishāsh, dan berperang). Pertama, pada soal puasa, khususnya dalam Q.S. al-Baqarah: 187, al-Qur`an bercerita tentang betapa tarikan keinginan nafsu manusia itu begitu kencang yang diungkapkan dengan “Allah mengetahui bahwa kalian tidak akan dapat menahan dirimu”; di sini redaksinya secara harfiah terbaca “…kalian akan ‘mengkhianati’ dirimu”, dalam pengertian tidak bisa menahan nafsu. Dari sini, al-Qur`an kemudian menyatakan Allah Swt mengampunimu dan memaafkan, sehingga kemudian dibolehkan menggauli istri pada malam hari (menurut riwayat, semula dibatasi hingga shalat Isya atau tidur) di bulan Ramadhān, berbeda dengan proses pensyariatan sebelumnya. Ada alasan kebolehan menggauli istri di malam hari Ramadhān yang dituangkan oleh ayat tersebut, yaitu karena “mereka (istri-istrimu) adalah (laksana) pakaian bagimu, dan kamu adalah (laksana) pakaian bagi mereka”. Ini adalah semacam filosofi yang mendasari kebolehan itu. Fungsi pakaian adalah menutupi atau melindungi. Sebagian tafsir menyebutkan bahwa maksudnya adalah pelindung dari berbuat zina atau masalah-masalah sosial. Di sini, kita bisa memahami bahwa Tuhan tidak ingin mematikan napsu, melainkan hanya disalurkan pada salurannya, atau dengan kata lain, dikendalikan, bukan dimatikan sama-sekali. Begitu juga, batasan lain dari penyaluran hasrat seksual adalah tidak mengganggu kegiatan i’tikāf di masjid. Itulah yang disebut al-Qur`an sebagai “batas-batas” (hudūd).
Kedua, terkait qishāsh. Lagi-lagi al-Qur`an menyentil tentang potensi ketakutan manusia pada kematian. Ini mungkin wajar, bahwa manusia takut mati. Akan tetapi, yang menjadi sasaran kritik al-Qur`an di sini adalah jika ketakutan akan bayangan kematian pada penegakkan qishāsh itu menjadikan orang kemudian hanya melihat sisi kematian. Padahal qishāsh adalah balasan karena adanya perlakuan yang sama; membunuh dibalas dengan hukuman bunuh, yang merdeka dengan yang merdeka, yang budak dengan yang budak juga, dan perempuan dengan perempuan juga. Ketakutan akan kematian berarti manusia mencintai hidup. Manusia tidak menyukai kematian, sesuatu yang tragis. Persepsi ini pastilah umum di benak orang ketika membayangkan kematian. Padahal, kasusnya berbeda pada qishāsh, karena kali ini kematian akibat di-qishāsh adalah balasan atas perbuatan yang serupa, sehingga hukumannya setimpal dan adil. Pandangan umum ini sebenarnya adalah tarikan nafsu, yaitu hanya mencintai kehidupan secara berlebihan dan menutup mata akan kenyataan bahwa qishāsh adalah sebuah cara yang digariskan oleh al-Qur`an, tidak hanya merupakan balasan setimpal, melainkan juga memiliki efek pendidikan bagi banyak orang. Orang akan berpikir ribuan kali untuk membunuh jika hukumannya juga dibunuh. Dengan berpikir seperti ini, maka pantas al-Qur`an menyatakan bahwa “Dalam qishāsh itu, ada (jaminan) kehidupan bagimu”. Dengan demikian, dalam pensyariatan qishāsh sebagai hal yang “diwajibkan” (kutiba), ada upaya al-Qur`an menekan potensi atau tarikan nafsu, yaitu kecintaan akan kehidupan secara berlebihan sehingga menggelapkan mata akan fakta bahwa qishāsh sesungguhnya bukan sekadar pembunuhan, melainkan “kehidupan” bagi nyawa-nyawa lain yang terlindungi sebagai efek pembelajaran dari penegakkan qishāsh, karena dengan begitu, kasus pembunuhan akan menurun. Meski persoalan qishāsh ini di diskusi kontemporer menimbulkan polemik, terutama jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), katakanlah sebagaimana dilontarkan oleh Thāha dan Abdullahi Ahmed an-Naim, setidaknya kita bisa memahami pesan hikmah yang tersurat dalam ayat itu.
Berbeda dengan soal puasa dan qishāsh di atas, maka dalam soal kewajiban berwasiat, al-Qur`an tidak secara eksplisit menyentil potensi nafsu manusia yang ingin ditekan. Namun, kita bisa memahami hal yang didiamkan (tidak diungkapkan) dalam ayat itu, namun banyak disinggung dalam beberapa ayat lain, yaitu kecintaan manusia secara berlebihan terhadap harta. Ayat yang tampaknya paling representatif sebagai ayat Q.S. al-Takātsur: 1–2 yang berbunyi: “Bermegah-megahan (berlomba-lomba memperbanyak/menimbun harta) telah menjadikanmu lalai, hingga kamu masuk ke dalam kubur”. Kecintaan terhadap materi, sejenis materialisme atau hedonisme, bisa menjadi potensi negatif yang menjadikan seseorang, hingga menjelang kematiannya sekalipun, untuk enggan berbagi kepada orang dekat sekalipun (kedua orangtua dan kerabat dekat). Atas dasar ini, al-Qur`an mensyariatkan wasiat bagi orang yang mendekati ajalnya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang terdekat. Syariat tentang wasiat, menurut pendapat sebagian ulama, tidak pernah dibatalkan (mansūkh) dengan ayat waris. Ulama klasik, semisal Imam al-Syāfi’ī dalam karyanya, al-Risālah, mensinyalir akan ada pembatalan itu. Namun, pendapat para ulama kontemporer menyebutkan bahwa baik ayat wasiat maupun ayat waris (Q.S. al-Nisā`: 11-12) sama-sama berlaku, tidak ada yang dibatalkan (mansūkh). Sama dengan kasus puasa, pada kasus pembagian harta ini, al-Qur`an lagi-lagi juga menegaskan bahwa ketentuan pembagian harta itu adalah “batas-batas” (hudūd) yang tidak boleh ditabrak (Q.S. al-Nisā`: 13–14). Di akhir ayat 12 sūrah ini, ketentuan itu disebut sebagai “ketentuan atau wasiat (washhiyyatan) dari Allah”. Pernyataan ini sangat tegas. Jadi, potensi napsu materialisme ini sangat ditekan oleh al-Qur`an. Bahkan, dalam sebuah hadīts, pesan ini lebih diperjelaskan. Seseorang yang mewasiatkan harta untuk orang-orang dekatnya atau ia meninggalkan harta untuk ahli waris akan khawatir bahwa harta peninggalannya itu akan menjadikan mereka kaya raya. Nabi Muhammad saw. malah menjawab bahwa menjadikan mereka kaya akan lebih baik daripada menjadikan mereka miskin, lalu meminta-minta kepada orang lain (HR. al-Bukhārī dan Muslim).
Ketiga, terkait berperang. Allah Swt. juga menekan potensi manusia akan kecintaan yang berlebihan pada dunia. Ini dianggap bahwa berperang untuk membela Islam sebagai hal yang tidak disukai, bahkan tidak baik. Dalam al-Qur`an (Q.S. al-Baqarah: 216), Tuhan menyentil anggapan keliru banyak orang bahwa meski perang diwajibkan (kutiba), namun banyak orang yang tidak menyukainya (kurhun lakum), sesuatu yang dianggap tidak baik, karena orang bisa terbunuh di medan perang. Anggapan ini tumbuh tentu dari ketakutan akan kematian, meski tujuannya sungguh mulia, yaitu membela Islam dari rong-rongan para pengganggu dakwah. Pikiran yang mendasarinya adalah sesuatu yang mendatangkan rasa sakit (kematian) adalah tidak baik. Jalan pikiran ini menghinggapi banyak orang yang dalam filsafat etika disebut sebagai etika utilitarianisme, yaitu sesuatu dinilai baik atas dasar utilitas (kebermanfaatan), sehingga jika dianggap tidak bermanfaat atau bahkan mendatangkan penderitaan, maka dianggap tidak baik. Di sini, ada relativitas dalam mengukur baik-buruk yang menghinggapi benak pikiran banyak orang. Banyak orang yang terperdaya dalam nalar yang relatif dalam menilai kebaikan. Al-Qur`an pasti menyadari anggapan semacam ini berkaitan dengan perintah berperang itu. Oleh karena itu, untuk membantahnya dan untuk menekan potensi nafsu manusia akan hedonisme kenikmatan hidup serta untuk menekan sesat berpikir soal standar kebaikan itu, lalu al-Qur`an mengemukakan kekeliruan berpikir itu “Boleh jadi, kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu”. Akhirnya, ayat ini ditutup dengan diktum “Allah-lah yang mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.
Ada satu kewajiban lagi, seperti halnya puasa dan kewajiban-kewajiban ini, di mana kata “ditulis” atau semaknanya digunakan, yaitu shalat (Q.s. al-Nisā`: 103). Ayat ini berbunyi “Sesungguhnya shalat adalah kewajiban (kitāban) yang ditentukan waktunya”. Kata “kitāban” (secara harfiah bermakna: “buku”, yaitu sesuatu yang ditulis, atau “ketentuan”) di sini diterjemahkan dengan “kewajiban”, seakar dengan susuan k-t-b dengan kata “kutiba” (ditulis, diwajibkan). Apa yang ingin ditekankan oleh al-Qur`an berkaitan dengan kewajiban shalat dalam pengendalian diri? Tidak ada pernyataan eksplisit dalam ayat itu. Namun, rangkaian ayat-ayat sebelum dan sesudahnya akan menuturkan kita “kegelisahan” al-Qur`an akan sifat manusia. Pertama, perlu diamati bahwa ayat ini berada dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya, terutama ayat 102 tentang shalat khauf, yaitu shalat ketika di medan perang, dan ayat sesudahnya (104) yang melarang kaum muslimin dari lemah semangat atau tidak punya nyali dalam mengejar musuh. Di ayat 107, al-Qur`an lagi-lagi menyinggung, sama pada kasus puasa di ayat Q.s. al-Baqarah: 187, tentang orang yang mengkhianati diri mereka sendiri (takhtānūna anfusakum), kini juga menyebut “jangan berdebat soal orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri” (yakhtānūn anfusahum). Ada kesamaan antara kedua redaksi di dua ayat berbeda itu, yaitu sama-sama konteksnya celaan atas kelemahan diri manusia. Pada kasus puasa, di ayat itu, manusia disebut mengkhianati diri mereka sendiri dalam pengertian tidak bisa menahan napsu jika bergaul dengan pasangan mereka di malam hari (setelah Isya/tidur) di bulan Ramadhān dilarang, sehingga Allah Swt. kemudian memberikan kemudahan dengan membolehkannya, namun dengan kata “mengampuni dan memaafkan” di dalamnya yang bermakna bahwa ketika itu pada fase awal disyariatkannya puasa memang tidak dibolehkan, hanya saja Allah Swt. kemudian memaafkan dan membolehkannya. Begitu juga, dalam Q.s. al-Nisā`: 107, al-Qur`an menyebut bahwa Allah swt tidak menyukai “orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri” (dalam kasusnya, adalah Thu’mah). Nabi kemudian dilarang membela Thu’mah beserta kerabatnya yang telah berkhianat itu.
Apa kaitannya dengan konteks beberapa rangkaian ayat-ayat sebelumnya tentang shalat? Dalam rangkaian ayat-ayat yang menyertai ayat perintah shalat itu, al-Qur`an secara implisit menyentil tentang pengendalian diri saat rasa takut menyergap, tepatnya di sini secara kontekstual, takut dari serangan musuh ketika peperangan berkecamuk. Rasa takut adalah perasaan yang sering menghinggapi manusia. Orang sering mengomentarinya, ini adalah suatu hal manusiawi. Semua orang mengalaminya dan ini adalah wajar. Namun, ada rasa takut yang muncul karena memang objek yang ditakuti begitu dahsyat, itulah Tuhan! Al-Qur`an mengungkapnya dengan kata khasy-yah, misalnya dalam ayat: “Orang-orang yang takut kepada Allah hanya orang-orang berilmu (‘ulamā`)”. Ada kalanya, takut itu muncul karena kelemahan diri dalam menghadapi suatu objek. Al-Qur`an mengungkapkannya dengan kata khauf. Setidaknya, pembedaan antara kedua kata ini pernah dijelaskan oleh Abū Hilāl al-‘Askarīy dalam al-Furūq al-Lughawīyah. Bisa jadi, kedua kata itu juga digunakan saling menggantikan maknanya (interchangable), misalnya kata khauf juga digunakan dalam kaitannya dengan Tuhan. Kembali ke soal rasa takut yang dimiliki oleh manusia tadi. Mungkin, ada rasa takut yang bisa dimengerti alasannya. Misalnya, rasa takut akan kematian akan ancaman kematian. Namun, ada rasa takut yang sulit dimengerti alasannya, karena hal-hal sepele, seperti seseorang takut keluar rumah karena ia menganggapnya ada hantu, padahal orang-orang lain tidak menganggapnya demikian! Jika demikian, maka rasa takut sebagian harus dikendalikan. Namun, apa yang mesti harus ditakuti dan yang yang tidak mesti ditakuti tentu sangat personal, atau bisa jadi terkadang sangat kultural. Lalu, agama (Islam) datang untuk menuntun dalam hal apa saja manusia perlu takut. Perang, di mana kematian akan membayangi setiap orang, tentu adalah hal yang umum ditakuti. Namun, al-Qur`an melalui syariat shalat khauf meletakkan rasa takut itu secara proporsional, yaitu pada tingkat waspada (terjaga). Oleh karena itu, dalam shalat khauf, rasa takut terhadap serangan mendadak dari musuh tidak menghalangi tetap didirikannya shalat, namun tetap waspada dengan formasi shalat sedemikian rupa (Q.s 4: 102). Yang dikritik oleh al-Qur`an kemudian, dalam konteks kepentingan agama Islam, pertama adalah rasa takut yang kemudian menghalangi perlawanan atau bahkan pembuntutan terhadap musuh (Q.s. 4: 104). Kedua, yang dikritik oleh al-Qur`an adalah rasa takut yang menghalangi orang yang beriman dari menegakkan shalat pada waktunya. Dalam konteks pengendalian diri atas rasa takut di situasi tidak aman seperti ini, pernyataan al-Qur`an bahwa shalat adalah “kewajiban yang ditentukan waktunya” itu harus dipahami. Shalat mutlak dilaksanakan kendati di situasi genting. Mungkin, ada orang berpikiran bahwa shalat di sitausi ini tidak perlu sama sekali dilakukan. Anggapan ini keliru, karena shalat sudah menjadi kewajiban (kitāban). Mungkin, ada orang beranggapan bahwa di situasi perang, shalat bisa ditunda. Anggapan ini keliru, karena shalat sudah ditentukan waktunya (mawqūtan). Dari berbagai konteks yang menyertainya, ayat tentang perintah shalat sebagai kewajiban yang telah “ditetapkan” (makna sesungguhnya dari “ditulis”) berisi tekanan terhadap potensi emosi negatif manusia, yaitu rasa takut yang menghalangi pelaksanaan kewajiban, dan tekanan terhadap pikiran “liar” akan tidak diwajibkannya shalat atau boleh dilaksanakan tidak pada waktunya.
Ikhtitām
Puasa, sebagaimana ditunjukkan dari penggunaan kata kutiba (ditulis) di dalam al-Qur`an, sebagaimana konotasi “ditulis” atau “termaktub”, adalah kewajiban yang ditetapkan secara kokoh. Kewajiban ini benang merahnya sama dengan kewajiban shalat, menegakkan qishāsh, dan berperang membela agama Islam yang ditetapkan sebagai ketentuan dari Tuhan. Penetapan secara kokoh itu bertujuan untuk mewujudkan pengendalian diri pada diri orang yang beriman. Dalam ayat-ayat di atas, tampak bahwa al-Qur`an menekankan pengendalian diri itu, seperti berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia akan makan dan minum serta kebutuhan seksual, dengan disyariatkannya kewajiban berpuasa. Tujuan ini juga sealur dengan pensyariatan lain, seperti pada shalat, qishāsh, dan kewajiban berperang. Tentu saja, kewajiban ini juga harus melihat konteks riil, seperti berperang hanya dimungkinkan karena alasan pembelaan (defensif). Puasa adalah sarana pengendalian diri, terutama terkait kebutuhan fisik, karena kebutuhan itu paling mendasar bagi manusia. Pengendalian itu bertujuan agar keimanan bisa termanifestasi secara nyata dalam beragama, sehingga ketakwaan yang menjadi ciri orang yang beriman bisa terwujud, karena bagian inti dalam menjalankan agama adalah pengendalian diri.
Banjarbaru, 6 Ramadhān 1445 H.


